ARTICLE AD BOX
Keterikatan masyarakat terhadap media karena empat fungsi pokoknya, yakni memberikan informasi, pengetahuan/pendidikan, hiburan, dan pengawasan. Fungsi ini tak hanya dilakoni pelbagai jenis media massa cetak (koran, majalah, sejenisnya), dan media elektronik (radio dan televisi), namun juga platform media digital.
Setiap media punya gaya mulai dari sajian informasi, pola artistik, dan citra gambar (foto, video, layout) yang ditampilkan. Gaya ini dapat menjadi representasi hingga tidak jarang menjadi rujukan bagi masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku. Di lain sisi, masyarakat dalam pelbagai kelompok atau komunitas, punya cara pandang tersendiri untuk memaknai peristiwa yang ditayangkan atau disiarkan oleh media massa. Oleh kerena itu, sajian media menjadi paradok. Sebab, apa yang benar menurut media, bisa dinilai salah menurut masyarakat. Sebaliknya, apa yang terkategori benar, baik, bagus, menurut masyarakat, tidak selalu menarik bagi media. Dari problematik tersebut, tulisan ini mencoba mengkaji tentang konstruksi pemberitaan media massa dalam perspektif sakralitas budaya di Bali.
Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) V, sakral = suci, keramat. Kata ini dapat diberi pengertian tentang entitas baik kebendaan dan nonmateriel yang tidak ternoda dan tidak tercemar dan dicemarkan secara niskala (nirtampak) dan sekala (tampak nyata). Dalam tradisi Hindu Bali, karena nilai kesakralan atau kesuciannya, maka sebuah entitas wajib dijaga, dihormati, diposisikan dalam ruang-ruang ekslusif; lebih tinggi, hulu/luan (atas), dan tak terjamah secara sembarangan. Namun, pemaknaan sakral atau suci tidak selalu terhubung dalam perspektif keagamaan. Sifat kesakralan juga bisa tersirat dalam pelbagai hal, baik wacana, teks, gagasan atau pola pikiran, dan yang lain.
Kata suci berikut pemaknaannya sangat familiar dalam praktik kehidupan masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Orang Bali menempatkan nilai-nilai kesucian, antara lain, melalui pemakaian sarana upakara Hindu Bali, ritual dalam pelbagai tingkat, hingga kesenian, yakni Tari Wali, Bebali, dan Balih-balihan. Tari Wali yakni tarian yang terkait langsung dengan pelaksanaan upacara. Misalkan, Tari Sanghyang Jaran, Tari Rejang Pingit, dan jenisnya. Tari Bebali, tarian yang fungsinya sebagai pelengkap pelaksanaan upacara. Misalkan, Topeng Pajeg atau Sidakarya. Dan, tari Balih-balihan yakni tarian atau pementasan kesenian yang bersifat tontonan untuk hiburan. Sedangkan profan adalah kondisi entitas yang di dalamnya tidak terkandung nilai-nilai kesucian atau sakral. Dalam pandangan Hindu Bali, profan bersifat leteh (tiada nilai suci atau kudus). Dalam konteks ruang, profan dimaknai berposisi di teben (bawah), dan cenderung inklusi.
Dalam hal pemberitaan media melalui perspektif kearifan lokal Bali, menjadi elok jika pemaknaan sakral – profan diposisikan dalam ruang yang harmoni. Kesakralan atau hal-hal yang berkenaan dengan kesucian, tentu bukan fenomena baru bagi masyarakat Hindu Bali. Praktik kesakralan tidak sekadar niatan untuk penguatan daya personal nan khusyuk dalam persembahyangan atau pun berupacara. Sakralitas juga menjadi bagian penting dalam menguatkan aura dewani atas persembahan kepada Yang Maha Pencipta. Terkait itu, pementasan kesenian Bali terutama jenis Tari Wali dan Bebali di kawasan pura, mrajan atau sanggah, adalah salah satu dari banyaknya proses untuk menguatkan daya batin personal dan aura suci pada lingkungan sekitar. Maka, dalam tradisi puja Hindu Bali, persembahan kesenian sakral atau tari wali, tidak hanya sekadar kewajiban. Persembahan tarian dengan pakem keindahannya menyatu menjadi kebutuhan untuk menguatkan kesucian atas persembahan kepada Ida Batara-batari.
Guna menguatkan nilai-nilai kesakralan seni budaya di Bali, maka fungsi media dalam pelbagai jelmaannya sangat penting. Melalui penayangan media, masyarakat dapat menemukan role model sekaligus batasan-batasan tentang seni yang bernuansa suci, atau sebaliknya yang profan. Namun, keragaman platform media disertai kemarakan konten digital dengan pelbagai informasi yang sedemikian bebas disiarkan/diposting, kerap memicu interpretasi. Keadaan ini secara tidak langsung terpicu oleh kian banyaknya sajian informasi yang tanpa ukuran jelas. Mana yang patut dan mana tidak patut, mana yang pantas dan mana tidak pantas, dan mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan kaidah agama dan perikehidupan sosial budaya masyarakat.
Keambiguan tersebut sejurus dengan kebebasan kemunculan media dalam pelbagai platform. Media tampak sangat bersaing ketat dalam merebut audiens (pembaca, penonton, pendengar untuk media arus utama/mainstream, seperti media cetak, TV, dan radio, dan like, viewer, subscriber untuk media digital). Dengan persaingan yang makin ketat ini maka fakta empirik yang muncul bahwa media kerap abai dalam penayangan konten yang dilandasi kaidah kesucian. Praktik dan pemaknaan sakral – profan oleh media cenderung berada dalam posisi abu-abu alias tidak jelas.
Ruang–ruang religius dan sakral makin tergilas oleh dominasi tayangan media yang profan dan atau sengaja diprofankan. Fenomena ini ditandai banyaknya konten-konten berbasis erotis yang menonjolkan selangkangan, sadistis atau kekerasan, dan hal-hal lain, sebagai daya tarik. Berita tentang pelanggaran kesucian, semisal palinggih pura yang diduduki wisatawan untuk berfoto selfi, amat cepat viral. Meteri berita yang memuat foto berikut narasinya secara benderang seperti ini mengingatkan kembali memori publik tentang arti dan makna kesucian yang terrampas oleh praktik sosial. Pada saat bersamaan media lebih selalu intens menyuapi publik dengan berita ‘berdaya tarik tinggi’ itu, sekaligus memenuhi kepentingan untuk merebut like, viewer, share, dan subscribed yang sebanyak-banyaknya.
Secara sadar, media selalu dirindukan karena fungsinya. Namun fakta yang sering muncul malah berbalik, bahwa dalam hal menjaga nilai-nilai kesakralan seni budaya Bali, media kerap lepas kontrol. Hal itu, antara lain, karena kurangnya pengetahuan para awak media tentang nilai-nilai kesakralan, terlebih pada wujud seni budaya yang disakralkan, sebagaimana dalam tradisi puja Hindu Bali. Kondisi ini menjadikan awak media tidak membayangkan bahwa media sebagai alat ungkap berupa tulisan, sajian layout koran/majalah (cetak atau online), dan tayangan videografi, bahkan foto-foto berita, mesti mematuhi kaidah-kaidah kesakralan.
Masyarakat secara umum menilai wartawan adalah insan profesional dengan basis pengetahuan relatif luas. Maka wartawan dianggap serba tahu tentang arti, konsep, dan makna entitas yang diberitakan, termasuk hal sakral dan profan. Padahal wartawan adalah manusia biasa yang dihadapkan pada persoalan sedemikian kompleks dan menjelimet. Tak sedikit awak media atau konten kreator media digital belum punya pengetahuan tentang sakralitas dan keprofanan. Bagaimana pula proses dan tata aturan mulai dari peliputan hingga penayangan hasil liputan. Awak media kebingungan mengidentifikasi mana objek liputan bernuansa sakral dan mana yang profan. Jurnalis sebagai manusia biasa punya punya sifat hakiki, yakni lelah, lesu, letih, dan aneka kelemahan daya fisik lain hingga dapat mengacaukan visi tentang sakralitas sebuah hasil liputan. Kondisi kian parah jika sistem kerja lapangan para jurnalis kian berat. Tambah parah lagi jika disertai ketakteraturan jam kerja hingga ketidakpastian beristirahat. Kelemahan fisik ini tentu berpengaruh pada kondisi psikis hingga guncangan mental. Jurnalis sulit menangkap materi liputan secara utuh, lebih-lebih materi bersifat khusus terutama pemaknaan tentang nilai-nilai sakralitas yang semestinya ada pada objek liputan. Maka tak jarang, menjadikan jurnalis senior sekalipun bisa mendadak bad mood bahkan kena mental block.
Era digitalisasi telah mengubah paradigma pemberitaan media dari kedalaman isi menuju kecepatan penayangan atau posting. Kondisi ini karena media, terutama media online, bahkan netizen, berlomba-lomba secara ketat untuk berburu respon audiens, berupa like, viewer, dan subscribe, yang makin banyak. Akibatnya, jurnalis hanya menyajikan informasi dangkal, tidak mampu menembus pada persoalan makna-makna objek diliput, lebih-lebih terkait nilai-nilai kesakralan. Dalam pemahaman positif, media bertugas menghadirkan realitas dari objek liputan. Namun dalam perspektif kritis, tidak mustahil realitas merupakan kenyataan semu karena dibentuk dengan semangat atau kekuatan pasar, kapitalis, dan kuasa dominan lainnya. Mengutip Stuart Hall dalam Ariyanto (2008), realitas tidaklah secara sederhana dapat dilihat sebagai satu set fakta, tetapi hasil dari ideologi atau pandangan tertentu.
Berangkat dari pemahaman itu, maka realitas yang ditampilkan media tidak terpisahkan dari konstruksi berupa agenda setting dalam politik keredaksian media. Oleh karenanya, media tidak sanggup untuk urati (peduli) atau sengaja melupakan kandungan norma-norma budaya lokal dalam pemberitaan, terutama hakikat kesakralan. Kebijakan redaksi lebih fokus pada eksistensinya melalui sistem manajemen industri, sebagaimana dikenal dalam pers industri. Maka, media berhak meraih pendapatan melalui jual tiras dan iklan atau advertorial untuk media cetak, atau iklan, dan monetisasi serta pendapatan lain yang sah.
Oleh karena itu, media sedapat mungkin untuk selalu merevitalisasi diri melalui peningkatan kualitas kerja, merekognisi pengetahuan dan baik bersifat modern dan tradisional. Sebagai bagian dari entitas publik, khususnya di Bali, media wajib dan berhak mempraktikkan pola-pola siaran berlandaskan kearifan lokal Bali berbasis agama Hindu, tidak terkecuali dimensi kesakralan seni budaya Bali. Media dengan pelbagai platform makin berorientasi pada percepatan tayangan/penyiaran hingga kerap sepanan (kalabakan) untuk membuat materi siaran yang didasari nilai-nilai kesakralan budaya. Para jurnalis, videografger, kreator konten, pekerja channel platform media, dan lainnya, sedapat mungkin disediakan ruang-ruang pembinaan yang lebih intensif. Antara lain, oleh pemerintah, instansi terkait, PHDI, Majelis Desa Adat, kampus bernuansa Hindu Bali, dan pihak-pihak yang urati menjaga nilai-nilai kesakralan Bali.* Oleh : I Nyoman Wilasa

 2 weeks ago
2
2 weeks ago
2






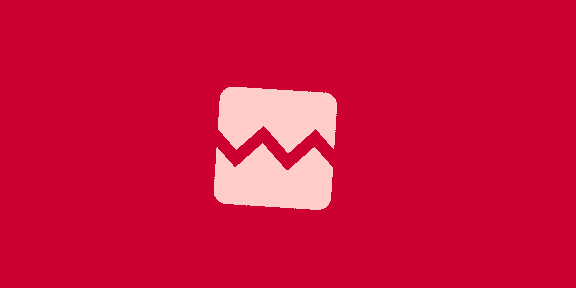

 English (US)
English (US)